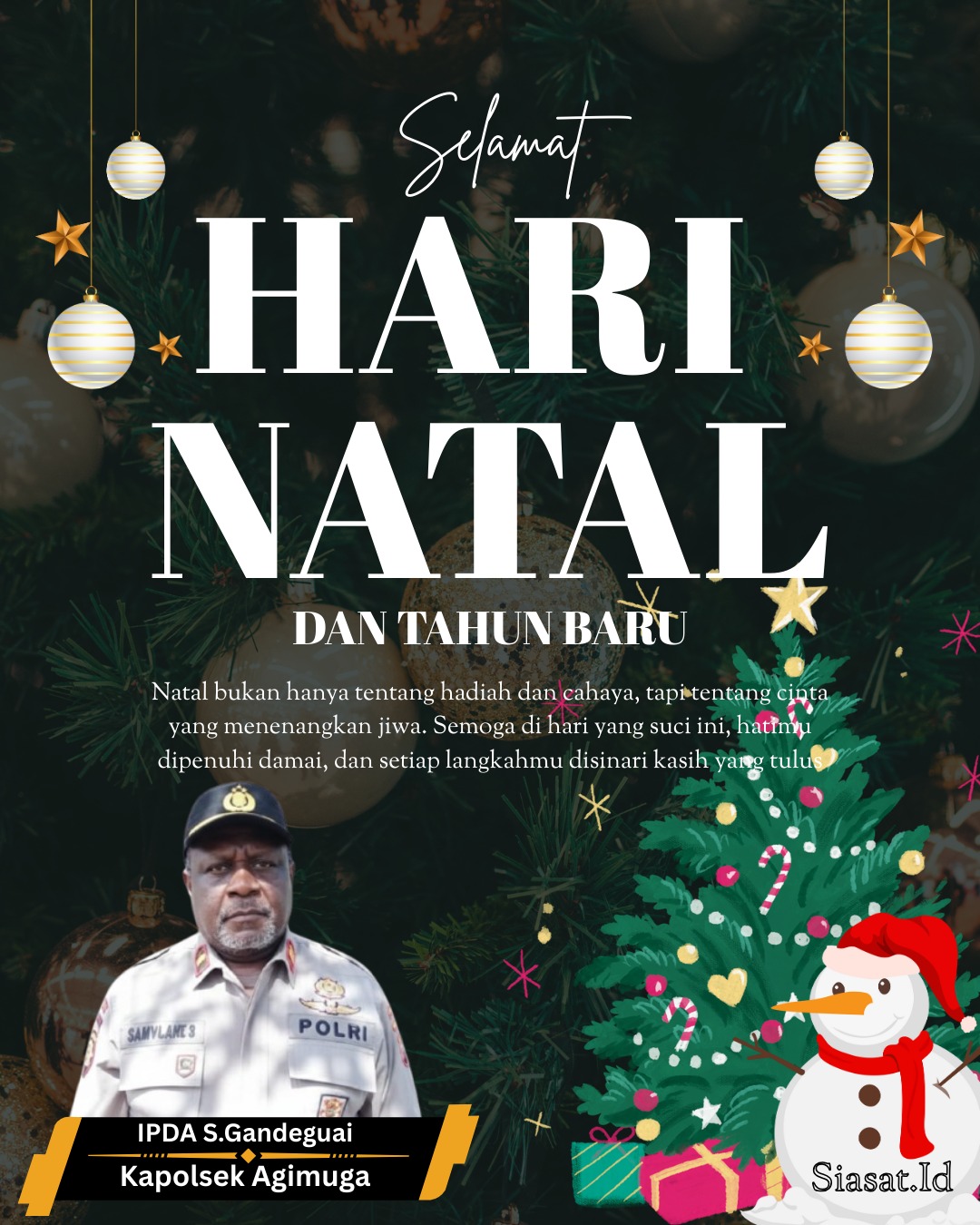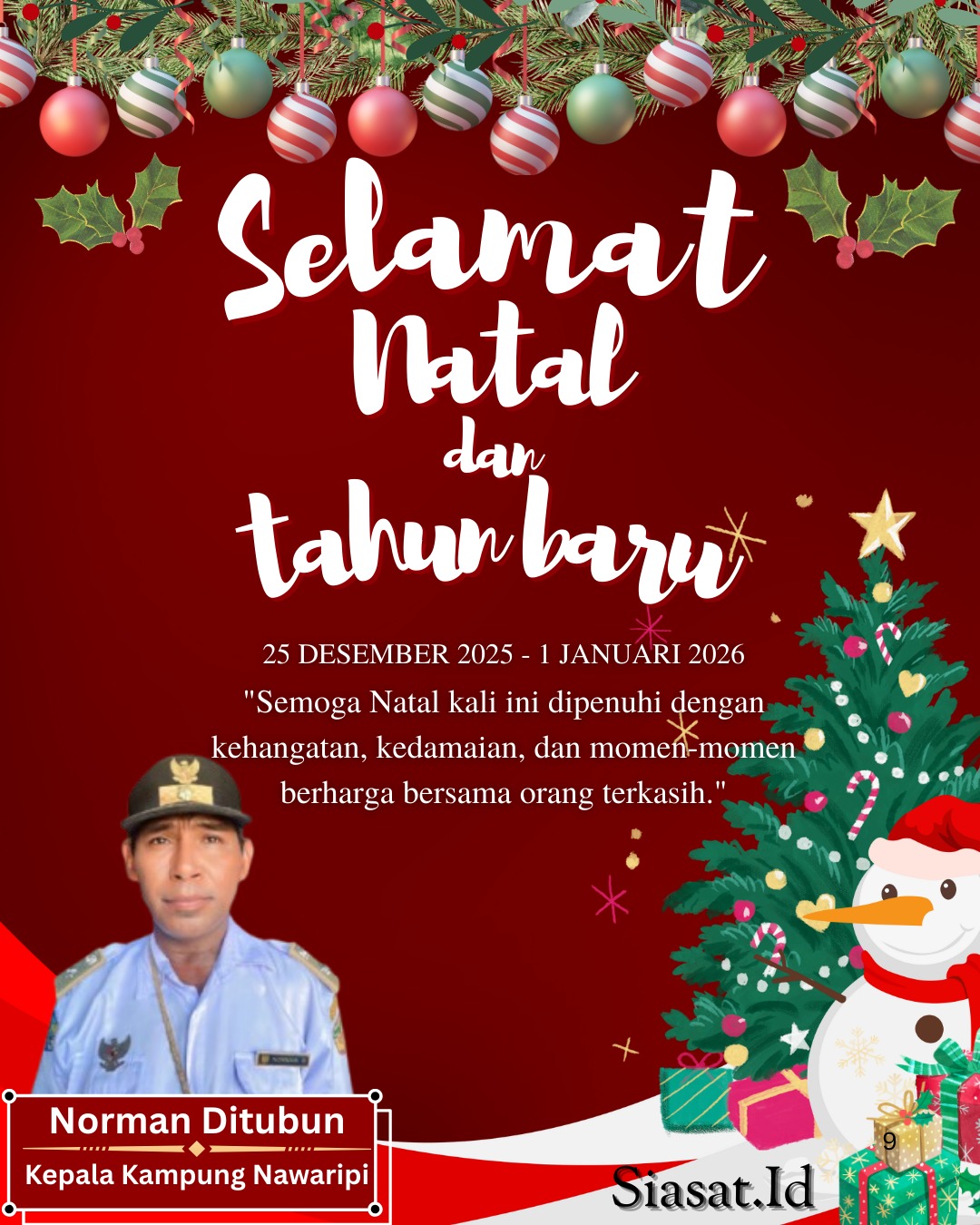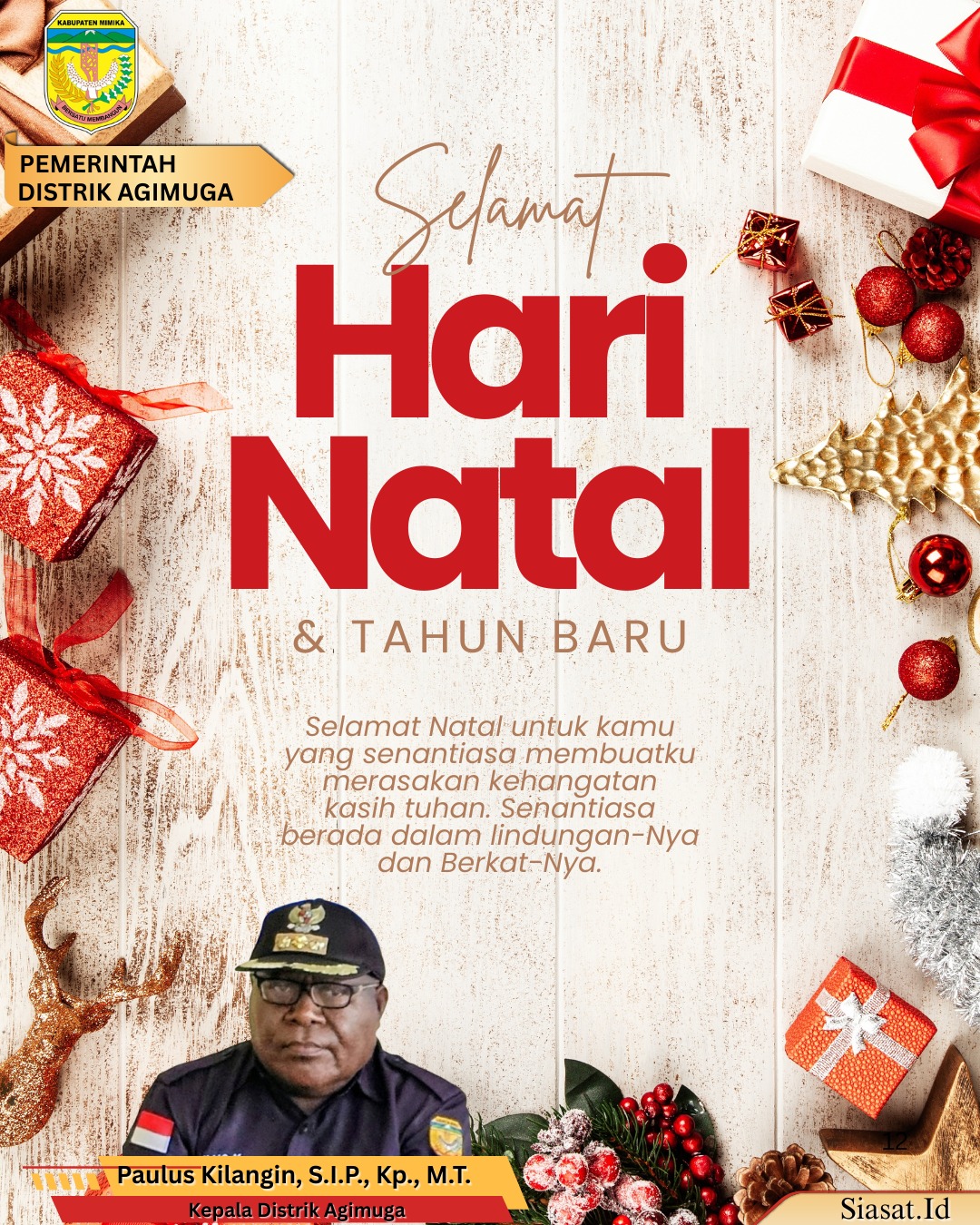Arief Rahzen, pekerja budaya
Agustusan di Manonjaya, sebuah kecamatan bersejarah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membawa lebih dari sekadar udara lembap khas Priangan. Ia membawa sebuah pertanyaan implisit yang menggantung di antara umbul-umbul merah putih yang terpasang di setiap gang: Apa sesungguhnya makna merdeka? Apakah ia sebatas upacara bendera yang khidmat di lapangan kecamatan, pidato pejabat yang didengarkan separuh hati, ataukah sesuatu yang lain? Jawaban paling jujur atas pertanyaan itu tidak ditemukan dalam seremoni formal, melainkan dalam riuh rendah dan peluh keringat perayaan yang diselenggarakan oleh rakyat itu sendiri. Pawai Agustusan di Manonjaya bukanlah sekadar festival. Pawai ini ialah sebuah manifesto hidup, sebuah tesis yang menegaskan gotong royong merupakan sistem operasi fundamental yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Narasi kemerdekaan ini tentu saja tidak dimulai pada tanggal tujuh belas, beberapa minggu sebelumnya di sebuah teras rumah seorang sesepuh desa. Di sanalah, di bawah cahaya bohlam 5 watt, mesin sosial itu dinyalakan. Tidak ada undangan rapat, hanya sebuah panggilan lisan yang menarik para pemuda pemudi, petani, pedagang, ojek hingga pegawai negeri. Ditemani kopi hitam dan singkong rebus, mereka tidak sedang rapat, mereka sedang merawat mimpi bersama. “Tahun kemarin kita buat replika Macan Siliwangi, bagaimana kalau tahun ini kita buat sesuatu yang lebih gagah? Tank!” usul Kang Ujang, matanya berapi-api. Tawa pecah. “Tank dari mana, Jang? Besinya mau cari di mana?” sahut Pak Didi, seorang petani. Pak Sobur, sambil mengisap rokok kreteknya dalam-dalam, menengahi dengan bijak. “Gagasan bagus. Tapi tank kita bukan dari besi. Tank kita terbuat dari bambu, semangat, dan kebersamaan. Itulah senjata kita yang sebenarnya.”
Malam itu, sebuah ide lahir bukan dari perintah, melainkan dari dialog. Inilah parlemen rakyat yang sesungguhnya. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada anggaran resmi, yang ada hanyalah modal sosial dan kebanggaan kolektif. Seketika, peran terbagi secara organik. Kang Ujang, dengan keahlian mekaniknya, ditunjuk sebagai “insinyur utama”. Bapak-bapak yang lain menjadi tim logistik, mencari bambu di kebun masing-masing. Para pemuda menjadi tenaga kerja kreatif. Dana operasional? Iuran sukarela, seikhlasnya, dari lima ribu hingga dua puluh ribu, dikumpulkan dalam kaleng biskuit bekas. Di sini, nilai kontribusi setiap warga tak diukur dari jumlah uang sumbangan, tapi dari kesediaan untuk menjadi “kita”.
Jika musyawarah warga adalah legislasi, maka minggu-minggu berikutnya adalah eksekusi bersama, sebuah alkimia sosial yang mengubah bahan-bahan seadanya menjadi simbol kebanggaan. Halaman rumah Kang Ujang sontak berubah menjadi bengkel kerja komunal. Aroma bambu yang dibelah berpadu dengan bau cat dan lem. Deru gerinda bersahutan dengan gelak tawa dan alunan musik dangdut dari radio butut. Proses ini adalah antitesis dari logika industri modern. Tidak ada mandor, tidak ada jam kerja, tidak ada upah. Orang-orang datang dan pergi silih berganti setelah mereka lelah bekerja di sawah atau pasar, menyumbangkan sisa tenaga mereka bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa memiliki.
Di tengah kesibukan itu, para ibu menjadi tulang punggung yang tak terlihat. Mereka tidak ikut menggergaji atau mengecat, namun tanpa logistik dari dapur mereka, mesin gotong royong ini pasti akan macet. Setiap sore dan malam, Ibu Aisyah dan tetangganya datang membawa nampan berisi gorengan hangat dan berteko-teko teh manis. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah energi, kepedulian, dan penegasan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, adalah vital. Anak-anak kecil yang berlarian di sekitar proyek Agustusan menjadi pewaris semangat ini. Mereka melihat langsung bagaimana sebuah tank yang gagah bisa lahir dari bilah-bilah bambu, bagaimana tawa ayah mereka bisa meringankan beban angkut yang berat. Mereka tidak diajari tentang gotong royong di kelas, mereka menghirup dan merasakannya secara langsung.
Pagi hari tanggal 17 Agustus, jalanan utama Manonjaya adalah panggung pembuktian. Setelah upacara resmi yang singkat di alun-alun kecamatan, barulah perayaan yang sesungguhnya meledak. Kontrasnya begitu tajam. Jika seremoni negara adalah tentang kepatuhan pada protokol, maka pawai rakyat adalah tentang ledakan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Di sinilah argumen utama menemukan wujud fisiknya. Ketika “Tank Bambu” dari desa Kang Ujang muncul dari tikungan jalan, didorong oleh belasan pemuda yang berpeluh dengan wajah berseri-seri, sorak-sorai membahana. Tank itu, dengan cat lorengnya yang sedikit belang dan meriam dari pipa paralon, mungkin terlihat lucu bagi mata sinis kaum urban. Namun bagi warga Manonjaya, ini monumen kerja keras mereka. Ini bukan sekadar properti karnaval. Ini bukti nyata bahwa dari ketiadaan materi, mereka bisa menciptakan sesuatu yang megah melalui kekuatan kolektif. Ini simbol kemandirian dan daya cipta, esensi sejati dari kata “merdeka”.
Pawai itu sendiri adalah sebuah teks berjalan tentang “Bhinneka Tunggal Ika” yang dipraktikkan, bukan sekadar dihafalkan. Ada rombongan petani membawa hasil bumi, ada barisan ibu-ibu berkebaya, ada kuda lumping, ada anak-anak madrasah yang menyanyikan selawat. Setiap kelompok menampilkan identitas uniknya, namun mereka semua bergerak dalam satu irama besar, merayakan satu narasi bersama. Batas antara peserta dan penonton kabur. Warga di pinggir jalan tidak hanya menonton, mereka berpartisipasi dengan sorakan, lambaian tangan, dan tawa. Ini adalah nasionalisme yang tumbuh dari akar rumput: hangat, inklusif, dan otentik. Inilah nasionalisme yang dirayakan karena cinta pada negara-bangsa.
Maka, pawai Agustusan di Manonjaya harus dibaca bukan sebagai festival semata, melainkan sebagai sebuah pernyataan sikap. Ini bantahan telak terhadap sinisme modern yang meremehkan gotong royong sebagai konsep usang. Di sini, gotong royong tampil bukan sebagai warisan budaya yang pasif, melainkan sebagai kekuatan rakyat. Ini cara rakyat merebut kembali hakikat kemerdekaan dari monopoli seremoni kenegaraan. Inilah bukti bahwa perayaan kemerdekaan yang paling otentik adalah yang lahir dari keringat rakyat, dimiliki oleh denyut nadi komunitas, bukan yang diatur dari podium kekuasaan.
Perayaan pada akhirnya memang akan usai. Bendera tergulung, panggung terbongkar, dan jalanan kembali pada rutinitasnya. Namun, gotong royong bukanlah panggung yang bisa dibongkar. Ia adalah fondasi yang semakin kokoh setelah ditempa kerja bersama. Di tengah zaman yang tembok-tembok individualismenya kian meninggi dan gema media sosial memecah belah kita dalam ruang-ruang sempit, praktik di Manonjaya ini bukan lagi sekadar nostalgia. Inilah vaksin sosial yang mendesak kita butuhkan untuk mencegah perpecahan. Inilah pengingat paling keras: fondasi republik ini sesungguhnya tidak ditopang oleh menara-menara baja di ibu kota, melainkan oleh musyawarah warga yang tergelar di teras-teras rumah sederhana, tempat warganya masih percaya pada kekuatan mimpi, dialog, dan kerja bersama. Tentu saja, berbagai desa di Indonesia juga merayakan semangat kebersamaan yang serupa. Di desa- desa inilah, denyut nadi keindonesiaan yang sejati dijaga agar tak berhenti berdetak.
Arief Rahzen, pekerja budaya yang meminati kajian budaya dan perubahan masyarakat di era digital. Sesekali menulis esai, bercerita, dan terlibat aktivitas budaya.